Paradoks Transisi Energi! Proyek LNG Bali Dinilai Abaikan Nelayan dan Ancam Ruang Hidup Pesisir
- account_circle Ray
- calendar_month 18 jam yang lalu
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DENPASAR – Di tengah euforia diskusi transisi energi Asia Tenggara menuju 2050 yang mengemuka dalam forum MIT ASEAN: Powering Southeast Asia Through 2050 di Bangkok, Agung Wirapramana yang dihubungi via whatsapp justru melihat potensi krisis transisi energi justru kehilangan prinsip keadilannya di Bali. Aksi turun ke laut nelayan Serangan pada 15 Januari 2026 menjadi alarm keras bahwa agenda besar dekarbonisasi nasional belum sepenuhnya berpihak pada realitas sosial di akar rumput.
Pengamat kebijakan energi, Agung Wirapramana, yang dihubungi di sela kehadiran nya pada event exclusive tersebut, menilai protes nelayan bukan sekadar penolakan teknis terhadap rencana pembangunan terminal LNG di Bali Selatan, melainkan sinyal kegagalan negara menjembatani ambisi ketahanan energi dengan kedaulatan ruang hidup masyarakat pesisir.
“Di forum ini, saya kebetulan sedang berdiskusi tentang proses transisi energi berkeadilan dan ESG, kita bicara target transisi 2050, tetapi di Serangan masyarakat bicara soal hari esok mereka. Ini menunjukkan adanya missing link serius dalam transisi energi,” ujar Agung saat dihubungi, Selasa (27/1).
Menurutnya, nelayan Serangan terkejut karena informasi terkait Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2832 Tahun 2025 justru mereka ketahui dari pemberitaan media, bukan dari proses dialog publik yang terbuka dan deliberatif. Situasi ini memperlihatkan transisi energi dijalankan secara elitis dan berpotensi menjadi beban sosial baru bagi masyarakat pesisir.
Surplus Listrik, Tapi LNG Tetap Dipaksakan
Agung juga menyoroti paradoks mendasar dalam kebijakan energi Bali. Saya kurang yakin namun katanya data menunjukkan bauran energi terbarukan Bali pada 2024 baru mencapai 2,7 persen, sementara ketergantungan pada energi fosil masih tinggi, dengan minyak bumi sebesar 27 persen dan batu bara 24 persen. Namun di sisi lain, laporan Oktober 2025 mencatat beban puncak listrik Bali hanya 1.260 MW dari kapasitas terpasang sekitar 1.500 MW.
“Dengan asumsi data tersebut, secara faktual Bali tidak dalam kondisi darurat listrik saat ini. Masih ada ruang napas. Maka wajar jika publik mempertanyakan urgensi LNG,” tegasnya.
Ia mengakui ancaman pemadaman massal di masa lalu menjadi trauma kolektif pemerintah. Namun, menurutnya, LNG tidak boleh dijadikan solusi permanen, apalagi gas alam tetap menghasilkan emisi metana dan membutuhkan konsumsi air besar dalam proses regasifikasi. “Gas seharusnya jembatan, bukan tujuan akhir yang justru mematikan inisiatif energi terbarukan,” katanya.
Risiko Tinggi di Jalur Penerbangan dan Kawasan Wisata
Penetapan lokasi Floating Storage Regasification Unit (FSRU) sejauh 3,5 kilometer dari Pantai Sidakarya juga dinilai belum ideal. Agung membandingkan jarak tersebut dengan terminal LNG di Lampung dan Jakarta yang berada 15 hingga 22 kilometer dari daratan.
“FSRU Bali Selatan berada tepat di bawah jalur penerbangan Bandara Ngurah Rai, hanya sekitar empat kilometer. Risiko kriogenik dan potensi kebakaran harus dihitung dengan standar Quantitative Risk Assessment yang sangat ketat,” ujarnya.
Selain risiko keselamatan, pengerukan alur laut hingga kedalaman 15 meter untuk kepentingan kapal LNG dinilai berpotensi memicu sedimentasi dan merusak terumbu karang di kawasan tersebut.
Benturan dengan KEK Kura Kura Bali
Masalah semakin kompleks karena Serangan tengah dikembangkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali yang berorientasi pada pariwisata marina berkelanjutan. Menurut Agung, menempatkan terminal LNG berskala besar di kawasan tersebut adalah kontradiksi kebijakan.
“Narasi ekonomi biru tidak akan masuk akal jika di saat yang sama kita merusak ekosistem laut dan habitat penyu yang menjadi ikon Serangan,” tegasnya.
Ia menilai keberadaan terminal LNG akan mengganggu akses navigasi nelayan tradisional sekaligus merusak lanskap pariwisata premium. Kondisi ini bertentangan dengan filosofi Tri Hita Karana yang selama ini dijadikan dasar pembangunan Bali.
Tiga Jalan Keluar dari Konflik
Agar proyek LNG tidak terus memicu konflik sosial, Agung mendorong pemerintah mengambil langkah korektif. Pertama, melakukan evaluasi serius terhadap lokasi alternatif di Bali Utara atau Timur, seperti Celukan Bawang, yang memiliki kedalaman laut alami dan jauh dari kepadatan pariwisata serta jalur penerbangan.
Kedua, mengubah pendekatan corporate social responsibility (CSR) dari sekadar kompensasi menjadi kemitraan strategis. Nelayan harus dilibatkan langsung dalam pengawasan lingkungan dan dijamin melalui skema asuransi jangka panjang.
Ketiga, pemerintah diminta lebih serius mengembangkan energi terbarukan berbasis komunitas melalui konsep Desa Berbasis Energi Terbarukan (DBET).
“LNG boleh saja menjadi jembatan, tetapi kedaulatan energi Bali di masa depan harus berada di tangan masyarakatnya sendiri. Transisi energi yang adil tidak boleh meninggalkan satu jukung nelayan pun,” pungkasnya.
Editor – Ray











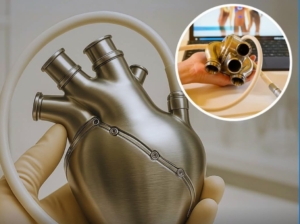





Promote our brand and watch your income grow—join today!
28 Januari 2026 3:37 PM